Salah satu pilar terpenting dalam reformasi perpajakan babak ketiga adalah penguatan teknologi informasi dan basis data. Pilar penting ini jelas mempunyai tujuan menjawab tantangan ekonomi digital yang meluas. Perjalanan panjang reformasi selama lebih dari 40 tahun sejak modernisasi peraturan pajak dimulai, menuntut administrasi pajak yang inklusif, efisien dan berkeadilan.
Di tengah ledakan transaksi lintas platform, platform global dengan mudah menjangkau pasar domestik, sementara pelaku lokal masih berjibaku dengan kompleksitas sistem dan beban administrasi. Maka, digitalisasi sistem administrasi pajak bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi penataan ulang strategi agar tidak ada pelaku usaha yang tertinggal.
Selama satu dekade terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah meluncurkan berbagai sistem berbasis TI seperti Sistem Informasi DJP (SIDJP), DJP-Online, hingga Coretax yang menjadi sisteman dalan mulai 2025. Di sisi pelayanan, perangkat e-filing, e-payment dan layanan swalayan daring menjadi andalan. Sedangkan untuk pengawasan, pendekatan berbasis risiko (compliance risk management/CRM) telah diterapkan.
Kecanggihan Coretax yang mengintegrasikan layanan administrasi pajak digital pun tidak menjamin keberhasilan jika tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia dan budaya digital. Wajib pajak (WP) masih menghadapi tantangan serius: kesulitan pengisian e-formulir, minimnya pemahaman hingga beban administrasi yang tinggi. Tanpa penyederhanaan dan dukungan literasi, digitalisasi justru bisa menjadi hambatan baru.
Tantangan digitalisasi
Tantangan pertama adalah kesiapan SDM. Dengan 44.000 pegawai DJP, distribusi masih dominan di fungsi administratif. Untuk mendukung administrasi digital, kompetensi SDM harus digeser ke arah teknis digital dan pemahaman atas dinamika bisnis modern. Pemetaan keterampilan telmologi informasi (TI) dan kemampuan analitik sangat diperlukan agar digitalisasi tidak hanya menjadi kosmetik kelembagaan. Kedua adalah budaya digital. Kompetensi digital tidak hanya harus dibuda yakan di internal DJP, tetapi juga di kalangan WP. Budaya ini tak tumbuh instan dibutuhkan komunikasi publik, pendampingan dan intervensi kebijakan lintas sektor agar literasi digital menjadi norma baru dalam pemenuhan kewajiban pajak. Ketiga adalah integrasi dan keamanan data.
Menteri Keuangan telah menegaskan pentingnya pertukaran data otomatis antarunit di lingkungan Kemenkeu. Hal ini harus menjadi fondasi dalam membangun sistem perpajakan yang transparan, adil dan berbasiskan data. Namun di saat bersamaan, kekhawatiran atas privasi dan keamanan data makin besar. Maka, prinsip transparansi harus dibarengi dengan jaminan akuntabilitas dan pembatasan penggunaan data di luar tujuan perpajakan.
Digitalisasi perpajakan bukan sekadar wacana. Langkah konkret sudah terlihat dalam regulasi pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Platform digital telah ditunjuk sebagai mungut PPN, dan mulai 2025, juga memungut PPh Pasal 22 atas pedagang yang berjualan di platform mereka. Kebijakan ini strategis, Informasi omzet WP dapat langsung diperoleh dari platform, membuka jalan bagi pengawasan yang lebih cerdas dan efisien. Di sinilah pentingnya keandalan sistem administrasi digital. Tanpa sistem yang solid, potensi penerimaan bisa bocor. Di sisi lain, WP Juga harus merasa sistem ini adil dan tidak memberatkan.
Membangun kepercayaan
Kunci sukses digitalisasi perpajakan bukan hanya pada sistem, tapi pada kepercayaan. Wajib pajak perlu merasa sistem ini berpihak: memberikan kemudahan, kepastian dan perlakuan yang setara. Jika tidak, kepatuhan sukarela yang menjadi tulang punggung sistem pajak akan terganggu.
Digitalisasi juga membuka peluang untuk strategi kepatuhan berbasis data. Dengan pemanfaatan analitik lanjutan dan kecerdasan buatan (AI), DJP dapat lebih presisi dalam menentukan target pemeriksaan dan menutup kesenjangan pajak.
Namun transformasi ini harus inklusif. WP skala kecil, seperti pelaku UMKM, perlu dukungan agar tidak tertinggal. Maka, digitalisasi juga harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mengurangi ketimparan, bukan memperlebar jurang antara pelaku usaha besar dan kecil. Literasi pajak digital harus dilakukan secara meluas antara kota besar dan wilayah pinggiran. Tanpa dukungan edukasi publik yang masif, wajib pajak di luar pusat ekonomi akan terus mengalami kesulitan akses dan pemahaman. Dalam konteks ini, DJP bersama pemerintah daerah perlu menjalin kolaborasi edukatif agar digitalisasi tidak menjadi sumber eksklusi. Jika tidak dikelola dengan cermat, digitalisasi justru dapat memperlebar jurang kepatuhan antara pelaku usaha yang memiliki akses teknologi dan literasi digital dengan mereka yang tertinggal secara infrastruktur maupun kapasitas.
Modernisasi sistem administrasi perpajakan bukan semata pembaruan teknis. Ini adalah upaya menata ulang hubungan fiskal antara negara dan warga negara di era digital. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan kompetisi, sistem pajak yang andal, transparan dan adil adalah kebutuhan mutlak.
Jika negara ingin memperkuat basis penerimaan, maka desain perpajakan digital harus menyentuh tiga hal: efisiensi, keadilan dan keberpihakan jangka panjang. Di tengah arus ekonomi digital yang tak mengenal batas, tantangan terbesar justru ada di dalam: bagaimana menjaga agar setiap rupiah yang dikumpulkan berasal dari sistem yang dipercaya, didukung dan dimiliki bersama oleh seluruh lapisan masyarakat.
Digitalisasi perpajakan adalah keniscayaan global. OECD dan negara-negara G20 pun menekankan perlunya pajak berbasis data dan platform lintas negara. Indonesia tidak bisa tertinggal, namun reformasi digital harus mengakar pada realitas domestik. Desain ulang sistem tidak cukup hanya efisien, tetapi juga harus adil, progresif dan menjamin keberlangsungan fiskal nasional di tengah perubahan ekonomi dunia.
Sumber : Harian Kontan, Jum;at 15 Agustus 2025, Hal 15.
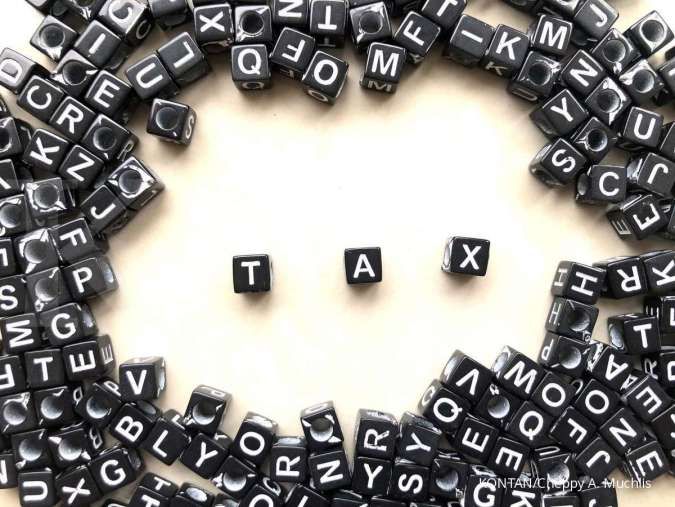
 WA only
WA only
Leave a Reply